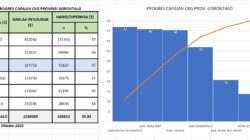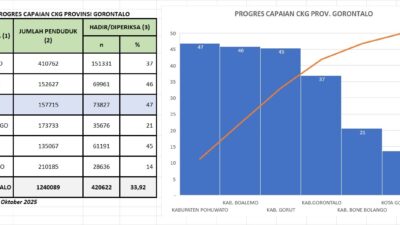READ.ID – Ada momen ketika lidah tersendat, dan dunia serentak menertawakan, itulah yang dialami Hariman Ibrahim (Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat). Sebuah video yang menampilkan dirinya gagap membaca teks Undang-Undang Dasar 1945 saat upacara Hari Kesaktian Pancasila beredar luas di media sosial, dalam sekejap potongan gambar itu menjadi bahan olok-olok.
Namun, seperti setiap potongan video viral yang tampak hanyalah satu sisi yaitu performa yang gagal, yang jarang dilihat dan tak tertangkap kamera adalah sisi manusiawi kisah hidup, ketulusan, dan spiritualitas.
Bagi masyarakat Pasangkayu, Hariman bukanlah pejabat yang jauh di menara kekuasaan, ia adalah bagian dari mereka, seorang nelayan yang meniti hidup dari laut, seorang pengusaha ikan yang membangun usahanya dari nol, seorang tetangga yang tak segan meminjamkan tenda atau elekton untuk pesta warga tanpa meminta bayaran. Dalam dunia politik yang kerap dipenuhi retorika tinggi, Hariman hadir dengan bahasa yang paling sederhana: tindakan.
Ia tidak piawai berorasi, tapi ia tahu cara mendengar. Ia tidak hafal pasal demi pasal, tapi ia paham arti berbagi. Bagi banyak orang, kepemimpinan seperti ini terasa langka ditengah politik yang sering menilai kecakapan dari kefasihan bicara.
Hariman mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati tak selalu datang dari podium; kadang, mereka muncul dari perahu kecil yang berlayar di laut.
Kecerdasan emosional mengajarkan bahwa kemampuan untuk mengenali perasaan diri dan orang lain, mengelola emosi, serta membangun hubungan sosial yang tulus adalah inti dari kepemimpinan efektif (Daniel Goleman 1995).
Hariman mungkin gagap di depan mikrofon, tetapi ia tidak pernah gagap dalam mengulurkan tangan, ia hadir di tengah masyarakat bukan karena strategi, melainkan karena panggilan empati. Ia memahami, bahwa didekati dengan hati jauh lebih efektif daripada dipimpin dengan suara lantang.
Dalam lanskap politik yang sibuk memoles citra, ia justru mempraktikkan kecerdasan emosional paling dasar: menjadi manusia yang hadir, bukan yang tampil.
Aspek lain yang Nampak dari peristiwa ini adalah kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk bertindak dengan makna dan nilai yang melampaui kepentingan diri (Zohar dan Marshall 2000), dalam konteks ini spiritualitas Hariman bukan terletak pada ritual, melainkan dalam etos berbagi yaitu semangat memberi bahkan ketika tak diminta.
Ketika videonya viral dan menjadi bahan tawa, Hariman memilih diam. Tidak membela diri, tidak marah, tidak menuduh siapa pun. Dalam diamnya, ada kebijaksanaan spiritual yang halus: kerendahan hati untuk menerima bahwa manusia tak pernah luput dari keterbatasan. Ia paham, mungkin tanpa teori, bahwa kadang-kadang yang paling fasih bukanlah kata, tapi ketulusan.
Peristiwa ini lebih dari sekadar “pejabat gagap membaca teks.” Ia adalah cermin sosial kita, betapa cepatnya kita menertawakan, betapa lambatnya kita memahami.
Kita hidup di zaman di mana kesalahan kecil bisa menenggelamkan kebaikan panjang, di mana satu momen di layar bisa menghapus puluhan tahun pengabdian. Fenomena ini menunjukkan defisit empati publik yang kian parah di ruang digital, kita cepat menghakimi, tapi enggan menyelami. Kita lupa bahwa di balik setiap kegagapan mungkin ada kisah manusia yang lebih dalam yaitu kisah tentang perjuangan, kerja keras, dan cinta pada sesama. Viralitas sering kali mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan, ia menjadikan manusia sekadar tontonan. Padahal, seperti kata filsuf Erving Goffman (1959), dunia sosial hanyalah panggung tempat kita semua kadang tampil baik, kadang tidak namun nilai sejati seseorang tidak terletak pada pertunjukan, melainkan pada niat yang menggerakkannya.
Sosok Hariman Ibrahim mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak harus lahir dari kelancaran berbicara, tetapi dari kemampuan menghadirkan diri secara emosional dan spiritual. Ia adalah contoh langka dari apa yang disebut kepemimpinan relasional, di mana hubungan antar manusia lebih penting daripada formalitas jabatan. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang seperti ini: yang mungkin terbata-bata dalam pidato, tapi jernih dalam niat; yang mungkin tak berpendidikan tinggi, tapi tinggi dalam empati.
Dunia digital mungkin telah menertawakan Hariman, tetapi masyarakat yang mengenalnya akan terus mengingatnya: bukan karena kefasihannya, melainkan karena ketulusannya yang bertahan.
Dalam budaya Bugis-Mandar, ada falsafah sipakatau (memanusiakan sesama), ada pula nilai siri’ na pacce, harga diri dan solidaritas. Dua nilai ini hidup dalam diri Hariman Ibrahim: sederhana, berani, dan peduli. Mungkin, inilah pesan spiritual paling kuat dari kasus ini, bahwa di tengah budaya politik yang penuh pencitraan, masih ada ruang bagi kesederhanaan. Bahwa dalam dunia yang haus kata-kata indah, ketulusan adalah satu-satunya bahasa yang tak membutuhkan penerjemah.
Kegagapan Hariman Ibrahim mungkin menjadi bahan tertawaan di ruang maya, tapi bagi mereka yang pernah mengenalnya, itu hanyalah fragmen kecil dari perjalanan panjang seorang manusia biasa yang dipanggil untuk mengabdi. Barangkali, di balik setiap jeda dan salah ucapnya, tersimpan pelajaran paling mendasar dari kemanusiaan bahwa yang sejati dari seorang pemimpin bukanlah kefasihan lidahnya, melainkan ketulusan hatinya.
Oleh [Fidi Mustafa, SKM., M.Si, Penasehat di Educare Institute]