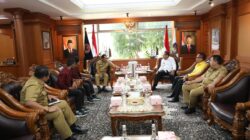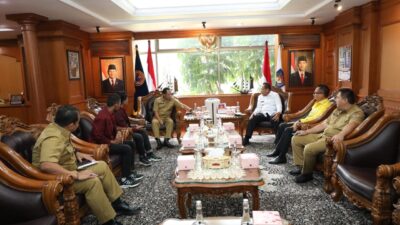READ.ID,- Jika menilik konteks politik Gorontalo saat ini, pernyataan Gubernur Gusnar Ismail tak bisa dilepaskan dari lanskap yang tengah bergolak. Setelah Pemilihan Ulang (PSU) Pilkada Gorontalo Utara memunculkan “pemenang yang kalah” dan memicu friksi antara aktor-aktor lama dan baru, dinamika politik ikut menjalar ke tingkat provinsi.
Sejumlah elite yang merasa kehilangan pengaruh pasca-Pilkada mulai memainkan narasi di media sosial, membangun persepsi bahwa pemerintahan Gusnar tak netral, atau bahkan “bermain dua kaki” dalam konstelasi lokal. Narasi ini berkembang liar, terutama di grup-grup WhatsApp politik dan akun-akun medsos yang punya afiliasi partisan.
Dalam lanskap seperti itu, diamnya Gusnar bisa dibaca sebagai bentuk counter-narrative ia tidak meladeni permainan lawan di medan yang mereka pilih. Tapi, bukan berarti ia tidak bergerak. Di Gorontalo, politik cenderung dijalankan lewat jejaring informal: keluarga, kampus, dan masjid. Kuliah Subuh bukan sekadar forum keagamaan, tapi juga panggung simbolik untuk menyampaikan pesan: “Saya masih pegang kendali.”
Ada yang menilai gaya Gusnar terlalu tenang untuk kondisi yang panas. Tapi, mereka lupa satu hal: Gorontalo bukan medan untuk politik frontal. Di sini, yang bergerak dalam diam justru yang paling mematikan. Seperti pepatah lokal bilang, “ta’a moloduwo, tapi ta’a momayayi” diam bukan berarti tidak berbuat.
Maka, jika hari ini Gusnar bicara soal solusi dan bukan drama, bisa jadi itu bukan hanya teguran untuk netizen, tapi juga peringatan untuk elite politik yang masih nyaman bermain di bayang-bayang keributan.
Sementara itu, masyarakat menonton. Dan seperti biasa: mereka tak selalu percaya siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tenang bekerja.****