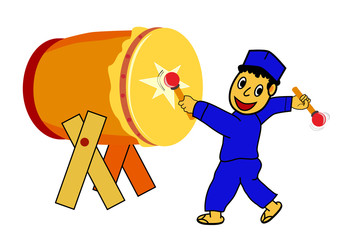Oleh: Muhammad Makmun Rasyid
Beduk masjid menjadi perakat umat saat bulan puasa Ramadan hadir. Momen inilah kita merasa bahagia, bersatu padu dan duduk berbasis sambil mengantri mengambil menu berbuka puasa. Dalam barisan itu, tidak lagi bertanya dari kelompok mana dan partai politik mana. Sama-sama tersenyum dan bersapa ria tanpa beban. Tapi saat berbuka puasa telah pergi dan mulai mengambil air wudhu, mulai kembali wajah ceria itu sirna sedikit demi sedikit. Berbuka puasa sebagai momentum merekatkan tali sesama umat Islam tidak membekas dalam hitungan menit.
Saat memasuki ruangan dalam masjid, terdengarlah bacaan demi bacaan ayat-ayat suci al-Qur’an yang juga kerap membius jiwa-jiwa yang di dalam dirinya masih ada iman. Bergetar jiwanya dan hatinya mulai menghayati satu persatu apa-apa yang terdengar. Ayat-ayat al-Qur’an bagaikan intan permata dan puisi tiada banding.
Usailah umat Muslim melaksanakan shalat Magrib, Isya dan rutinitas tarawih-witir. Satu persatu bergegas menuju halaman masjid untuk mendengarkan penceramah. Dalam rangka perayaan Nuzulul Qur’an itulah, masyarakat selalu disuguhi ragam dalil pentingnya Nuzulul Qur’an. Mulai dari pesan turunnya al-Qur’an, pesan esoterik dan eksoteriknya, pesan toleransi di dalamnya dan pesan baik lainnya. Namun sangat jarang yang berceramah menyuguhi hakikat dan orientasi masa depan umat dengan tujuan Allah memfirmankan kata “bacalah” (iqra’). “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam” (Qs. Al-‘Alaq [96]: 1-4).
Itulah jamuan pertama Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril AS. Banyak yang menelan begitu saja jamuan itu tanpa memaknainya secara mendalam. Bukan tanpa sebab, kata “bacalah” yang tidak disertai objek itu dan bermakna umum disajikan menunjukkan bahwa dalam setiap saat diperintahkan untuk membaca, menelaah, memahaminya, mengamalkannya bahkan menuliskannya.
Ayat perintah membaca itu harus dikupas satu persatu. Jika sebuah ayat diibaratkan sebuah bawang, ia memiliki lapisan demi lapisan. Maka menelan bawang tanpa membuka sampulnya yang berlapis-lapis membuat seseorang akan merasakan keanehan tersendiri. Begitulah al-Qur’an, tidak diperbolehkan menelannya mentah-mentah tanpa mendarasnya penuh keteguhan.
Dalam kajian-kajian tafsir al-Qur’an, setidaknya para mufasir menyuguhkan empat makna di dalamnya. Pertama, kata bacalah memuat aspek lahiriyah. Membaca apa saja yang tampak di depan matanya. Bahkan sesekali hanya menyentuh kulit teks itu, alih-alih mendalaminya. Orang dalam tahap ini, umumnya kaum Muslimin. Tujuannya hanyalah mengkhatamkan dan tak luput pula ada aura tersendiri, jika berkali-kali mengkhatamkan bacaannya, seperti menjadi Muslim sejati. Perlu diingat, Islam selalu mengiringi dua aspek, membaca-menulis dan mengamalkannya.
Kedua, membaca dengan benar dan baik atau istilah Nasaruddin Umar tahapan “how to read”. Dalam konteks al-Qur’an, maka bacalah al-Qur’an dengan bacaan yang setartil-tartilnya. Tidak saja tartil, tapi setartil-tartilnya. “Dan bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya (Qs. Al-Muzammil [73]: 4). Maka membaca al-Qur’an pada tahap ini harus benar-benar berkualitas. Yang menurut Imam Ali bin Abi Thalib, “membaguskan bacaan huruf-huruf al-Qur’an dan mengetahui hal ihwal berhentinya” (tajwîdu al-Hurûf w ma’rifatu al-Wuqûf).
Setelah membaca dengan fasih, tahapan berikutnya mendalami satu ayat ke ayat lainnya. Sebagaimana yang diutarakan Abdullah Darraz, seorang penulis kitab Al-Naba’ Al-Azhim (1974), bahwa “Ayat-ayat Al-Qur’an bagaikan intan. Setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut yang lain. Tidak mustahil, jika kita menyilakan orang lain mendengarnya, maka ia akan melihat lebih banyak ketimbang apa yang kita lihat.” Lebih lanjut, Sayyed Hossein Nasr—yang pemikiran dan buku-bukunya menyita waktu para mufasir Al-Qur’an untuk meneliti mantra-mantra tulisannya—menyatakan: “jika Nabi Muhammad SAW adalah mata air dari spiritualitas Islam, maka Al-Qur’an bagaikan halilintar yang setelah menyambar kontak listrik manusia, membuat mata air itu memancar keluar, seperti air yang turun dari langit yang menyebabkan sungai-sungai mengalir dari mata air tersebut.”
Keanekaragaman sinar yang terpancar dari setiap ayat-ayat Al-Qur’an membuat sebagian masyarakat Arab tatkala itu menyebut Nabi Muhammad sebagai pembawa-—bahkan lebih dari itu, yakni membuat dan mengarang—mantra dan sihir. Karena memang Al-Qur’an, secara jujur ia terasa magis, layaknya bahasa mantra. Ia juga kadang dilihat kitab puitik, disebabkan rima-rimanya teratur, inilah yang membuat pembacanya bergetar dan merinding.
Tapi apakah Al-Qur’an kitab sastra? Tidak sekedar kitab sastra. Tapi, Al-Qur’an mampu loncat secara revolusioner dari mainstream kepenyairan masyarakat Arab saat itu. Al-Qur’an telah mengalami tranformasi dari “the idea of God” menuju “Al-Kalam Al-Lafdzi”. Dengan menggunakan konsep Qs. Ibrahim [14]: 4, Al-Qur’an ingin menegaskan dirinya, secara sosiokultural erat kaitannya dengan bahasa dan budaya Arab, tempat ia diturunkan oleh Tuhan.
Kemudian, bahasa (Al-Qur’an) tidak saja “a way of speaking”, tapi “a way of reasoning”. Ini yang saya sebut, Al-Qur’an sungguh berada di atas sekedar kitab sastra. Para pakar Al-Qur’an selalu mengatakan, Al-Qur’an secara konseptual menawarkan nalar kebudayaan baru dan menggugat nalar kebudayaan lama. Ini sejalan dengan gagasan Qs. Al-Baqarah [2]: 3. Artinya, Al-Qur’an kitab yang kerap membangun nalar dunia makna. Saya ambil contoh kata “Allah”. Oleh para sastrawan tatkala itu bukan tidak ada di dalam tulisan-tulisan mereka. Tapi, mengapa Al-Qur’an mengatakan mereka orang yang gagal paham (baca Qs. Al-Ankabut [29]: 61), karena mereka tetap menyembah objek-objek lainnya, mereka tidak bisa menyembah Allah semata (Qs. Al-Ankabut [29]: 63).
Dasar argumentasi itu membawa kita tambah menjeburkan lebih dalam lagi, yakni ke wilayah emosional sebagai syarat menuju pembukaan tabir hakiki atas setiap teks al-Qur’an. Tentunya, posisi ketiga dan keempat ini sangat jarang kita temui. Keselarasan antara pembacaan dan pengalaman bisa serta kebersihan jiwa membimbing ke wilayah sana.
Penyingkapan hakikat Iqra’ tidak menyertai perayaan-perayaan Nuzulul Qur’an, kecuali mereka para penceramah yang betul-betul mengaji tafsir al-Qur’an dan mendalaminya. Pengungkapan ini, hemat penulis, agar masyarakat terbuka lebar bahwa perintah firman-Nya yang pertama itu dibutuhkan keberlanjutan dan membentuk dalam sebuah budaya. Ibaratnya, mengaji al-Qur’an tidak saja di bulan Ramadan dengan ragam iming-iming pahala, tapi di luar ramadan pun harus dibaca dengan pahalanya yang telah disediakan. Tidak saja mengkhatamkan di bulan Ramadan, tapi diluar Ramadan juga.
Keberlanjutan membacanya digambarkan Mohammad Iqbal, seorang pejuang Pakistan dan salah satu pemikir Islam modern berkata, “Bacalah al-Qur`an seakan-akan ia turun padamu”. Seakan-akan al-Qur’an diturunkan di masa kita dan untuk kita, sampai-sampai ada kerinduan tersendiri dan selalu ingin bercinta dengan al-Qur’an.
Disisi lain, Muhammad Abduh pernah berpesan kepada para muridnya: “rasakan keagungan al-Qur`an, sebelum kau menyentuhnya dengan nalarmu”. Ini lebih berat lagi, setelah membaca sebuah objek, kita merasakan getaran dan pantulan-pantulan sinar Ilahiyah itu sendiri, kemudian menggunakan nalar untuk menyibak tabir kegaiban dalam diri teks itu sendiri. Tentunya ini pula yang dimaksud oleh Imam al-Maududi, “Untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat al-Qur`an tidaklah cukup kau membacanya empat kali”.
Kata “bacalah” dalam jamuan pertama itu diikat oleh jamuan berikutnya, yakni “Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis” (Qs. Al-Qalam [68]: 1). Dua paket yang saling menopang, membaca dan menulis. Tapi umumnya masyarakat Indonesia, membaca-menulis tidak dibudayakan, sedangkan yang menjadi budaya adalah berbicara dan berkarlota. Walaupun tidak salah, tapi hanya negara yang literasi (membaca-menulis)-nya baik akan menghantarkan kepada perabadan yang baik.
Lemahnya kemampuan membaca-menulis dan di sisi lain tampilnya orang-orang baik tapi tidak pintar membuat permainan dunia semakin tidak mudah terkendali. Mengapa? Sebab rusaknya berita-berita dan pemelintiran berita-berita itu dilakukan oleh orang-orang pintar yang tidak benar dan dikonsumsi oleh orang-orang baik yang tidak pintar. Yang pintar tapi tidak benar karena spirit “bacalah” dan “menulislah” tidak tersingkap olehnya sisi spiritual dan belum terbuka olehnya tabir dari Allah serta ketiadaan hidayah. Adapun yang kedua, orang baik dan salih tapi malas membaca, selalu mengedepankan prasangka baik, akhirnya dimanfaatkan dan dikendalikan oleh jenis orang pertama tadi.
Dalam tradisi menulis inilah, telah banyak dicontohkan oleh para ulama-ulama klasik. Menulis sambil berpuasa memiliki rasa dan suasana tersendiri, yang berbeda dengan hari-hari biasa.
Seorang syaikh asal Sudan, Syaikh Bashir Mohammad Bashir berpuasa berbicara. Ia memutuskan tidak berbicara selama 25 tahun lamanya. Sejak saat itu ia pun dijuluki “silent syaikh”. Sebagaimana yang dilansir oleh Al-Arabiya (25/02/2015), Syaikh Bashir berkomunikasi dengan menuliskan apa yang ingin dikatakan di atas kertas putih. “Saya menggunakan pulpen saya hanya untuk menulis yang menyenangkan hati sahabat saya. Saya menemukan ketenangan pikiran dalam keheningan,” tambahnya. Ini berpuasa yang sungguh bermakna.
Kitab Syarh Al-Baiqûni fî Mustalah ‘Ilm Al-Hadîs disalin oleh Husain bin Al-Marhum Abu Bakar Al-Asyi dan kitab Bidâyat Al-Mubtadi bi-Fadhli Allah Al-Muhdi yang keduanya disalin di bulan puasa. Begitu pula kitab Qatr Al-Nidâ’ karya ulama Arab Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad ibn Yusuf ibn Hisyam Al-Anshari, yang disalin oleh Leube Adam Amud pada hari Senin, 25 Ramadhan, masa Sultan ‘Alauddin Muhammad Syah. Dan banyak lagi kitab-kitab dan buku-buku yang ditulis selama bulan puasa.
Pesan yang ingin disampaikan pada beberapa hal di atas adalah aktivitas selama bulan puasa jangan mengendor, justru slogan puasa meningkatkan kesehatan menjadi sarana seseorang untuk lebih giat dan meningkatkan kreativitasnya. Bagi penulis buku, minimal satu buku dituliskannya selama puasa. Usai membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, pastinya ia mendapat siraman rohani dan ide-ide bagus yang patut dituliskannya. Sebagaimana pengalaman penulis saat menulis naskah The Five Principles of Life ditulis selama bulan puasa tahun 2016.
Akhirnya, sebagai sebuah harapan, sebagai umat Muslim kita tidak sekedar merayakan Nuzulul Qur’an sebagai rutinitas sederhana, namun harus memaknai firman yang pertama turun untuk memajukan negara kita yang masih ketinggalan dalam bidang literasi. Kemanjuan ilmu pengetahuan menjadi syarat kemajuan sebuah bangsa. Selamat berbuka puasa!