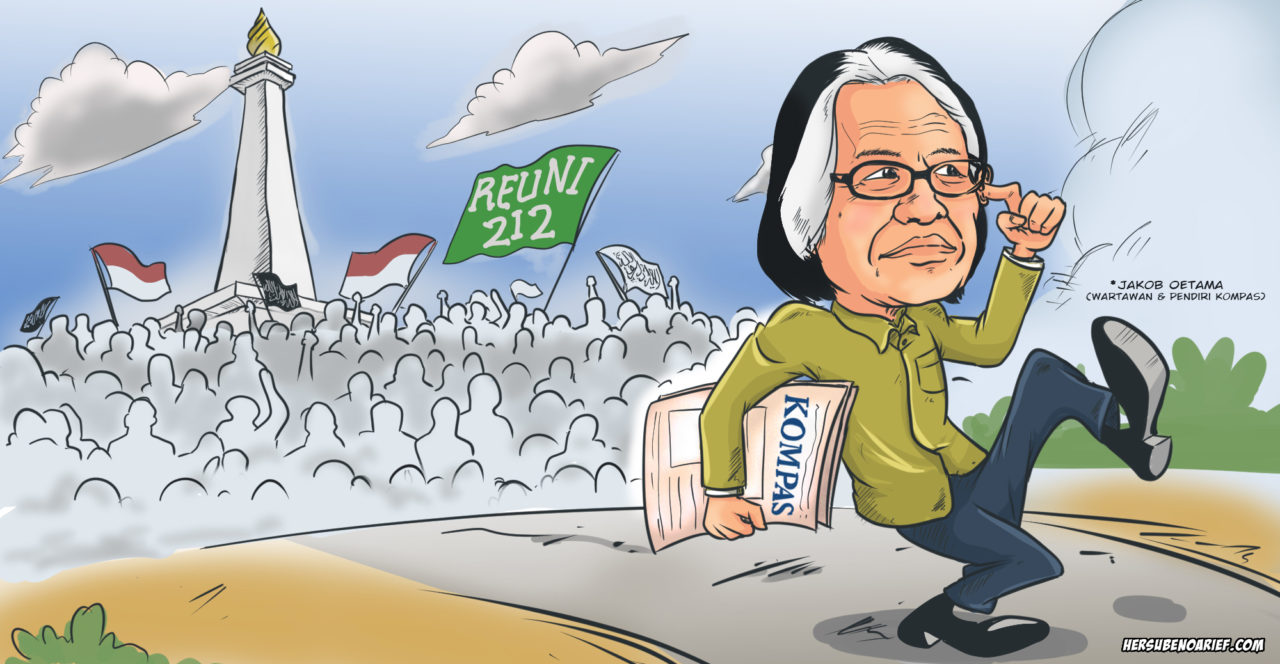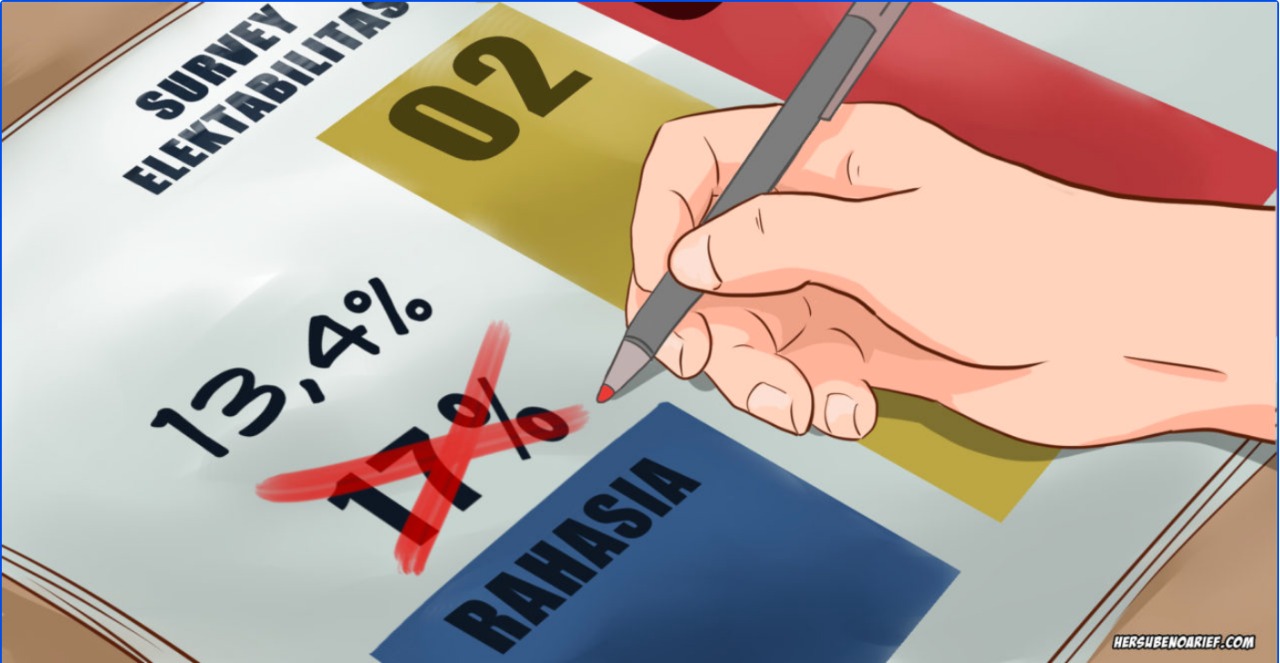Oleh : Hersubeno Arief
“Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tapi mengkritik orang yang sedang berkuasa.”
—P.K. Ojong—
Kutipan statemen tegas dan gagah dari pendiri Harian Umum Kompas itu dalam beberapa hari ini menyebar cepat di media sosial (medsos). Setelah ditelusuri pernyataan lengkapnya berbunyi:
”Secara intituitif setiap orang merasakan bahwa tugas utama pers adalah mengontrol dan kalau perlu mengecam pemerintah. Wartawan jangan sekali-sekali meminta dan menerima fasilitas dari pejabat. Sekali hal itu terjadi, ia tidak bebas lagi menghadapi pejabat itu dalam profesinya. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa tapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa.”
Pesan dari P.K. Ojong itu sungguh dahsyat. Sebuah kredo yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh wartawan Kompas, namun semua wartawan di seluruh dunia. Independensi, sikap kritis, fungsi kontrol, menjaga jarak dari kepentingan bisnis dan kekuasaan, membela keadilan, menyuarakan kebenaran adalah “ayat suci” yang harus dijunjung tinggi media, maupun seorang wartawan.
Apa boleh buat dengan kredo semacam itu pilihan hidup menjadi seorang wartawan mirip laku asketisme. Suatu gaya hidup bercirikan laku-tirakat atau berpantang kenikmatan-kenikmatan duniawi, yang seringkali dilakukan untuk mencapai maksud-maksud rohani. Jadilah profesi wartawan itu mirip-mirip dengan ulama, pendeta, atau tokoh agama lainnya.
Semua prinsip-prinsip ideal itu saat ini ramai dipertanyakan. Apakah Kompas sudah bergeser idealismenya? Apakah petuah pendiri Kompas itu telah berubah menjadi slogan kosong yang tidak lagi berarti?
Pilihan Kompas tidak untuk menampilkan Reuni 212 di halaman muka menimbulkan pertanyaan, bahkan gugatan. Di medsos bergema seruan untuk memboikot Kompas, bahkan ada yang menyatakan langsung berhenti berlangganan.
Apakah Kompas menganggap peristiwa luar biasa itu bukan sebuah peristiwa penting? Tidak ada nilai beritanya? Atau Kompas sengaja “meniadakan” peristiwa itu karena adanya perbedaan kepentingan ideologi dan politik?
Halaman muka adalah etalase sekaligus kebijakan politik redaksi (Editorial policy). Apa yang dinilai penting dan tidak penting, bagaimana sikap dan penyikapan, serta pilihan politik redaksi, dapat terlihat dari halaman muka.
Secara bisnis (jualan) halaman muka diperuntukkan untuk berita yang diperkirakan akan dapat mengangkat tiras sebuah media. Di tengah terus menurunnya tiras media cetak, peristiwa di Monas tentu tak boleh dilewatkan begitu saja. Jutaan orang berkumpul di Monas rasanya terlalu naif, atau bodoh malahan, untuk diabaikan sebagai pasar yang bisa dibidik. Kecuali, Kompas memang sudah punya pilihan dan penyikapan politik yang berseberangan dengan Reuni 212.
Kompas edisi Senin (3/12) ternyata memilih menurunkan berita utama tentang ancaman polusi sampah plastik. Berita Reuni 212 hanya ditempatkan di halaman 15 dengan porsi pemberitaan yang kecil. Halaman 15 atau halaman umum, adalah halaman sambungan dan berita lain yang tidak terlalu penting. Cukup asal ada saja.
Redaksi Kompas bisa berkilah bahwa setiap Senin mereka menyiapkan agenda setting. Sebuah pilihan atas topik-topik penting yang agendanya perlu didesakkan kepada publik. Topik semacam ini biasanya disiapkan jauh-jauh hari untuk menyiasati kekosongan berita pada akhir pekan. Sifatnya timeless, tidak mementingkan aktualitas. Bisa ditayangkan kapan saja.
Rasanya terlalu naif bila redaksi Kompas tidak mengetahui bahwa pada tanggal 2 Desember akan ada agenda tahunan Reuni 212. Secara jurnalistik peristiwa itu jelas merupakan peristiwa penting. Ada sekelompok, ribuan, bahkan jutaan orang berkumpul di Monas memperingati sebuah peristiwa bersejarah, Aksi 212. Sebuah peristiwa terbesar dalam sejarah protes massa yang pernah terjadi di Indonesia.
Ketika muncul gugatan terhadap Kompas, banyak yang membela dengan dalih kebebasan redaksi. Mereka bebas menentukan apa yang dimuat, dan apa yang tidak dimuat. Pertanyaannya? Kebebasan macam apa bila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip jurnalisme universal?
Ulama berpengaruh Abdullah Gymnastiar dalam program ILC menyatakan lepas dari afiliasi politik maupun agamanya, massa ini berkumpul menyuarakan ketidakadilan (perceive unjustice). Umat Islam menurut Aa Gym merasa sakit hatinya disebut radikal, intoleran, ingin memisahkan diri, anti NKRI dan berbagai stigma negatif lainnya.
Perasaan yang sama itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun ke Monas. Banyak diantaranya yang berasal daerah dan luar negeri sudah sejak lama menabung, menyiapkan bekal untuk hadir.
Dalam perspektif politik Jawa, apa yang dilakukan oleh massa Reuni 212 itu sama seperti laku “topo pepe.” Sebuah protes terhadap raja yang dilakukan dengan cara berjemur dan berdiam diri di alun-alun depan istana. Bedanya seorang Raja Jawa akan menemui para pemrotes, dan menampung aspirasinya. Sementara Jokowi memilih meninggalkan istana atau dalam bahasa Jawa disebut nglungani, dan melakukan “blusukan” di Bogor, Jabar.
Filosof dan aktivis demokrasi Rocky Gerung (Roger) menyatakan peristiwa itu settingnya sama dengan ketika pejuang hak-hak sipil AS Marthin Luther King memimpin ratusan ribu orang melakukan protes menuntut persamaan hak di Washington DC pada tanggal 28 Agustus 1963. Jika peristiwa Aksi 212 pada 2 Desember 2016 merupakan sebuah momen, maka Reuni 212 yang terjadi Ahad lalu telah menjadi monumen.
Sikap sejumlah media termasuk Kompas yang mencoba “menenggelamkan” peristiwa sangat dikecam oleh Roger. Secara keras dia menyebutnya sebagai Penggelapan sejarah!
Sebagai sebuah peristiwa, Reuni 212 jelas merupakan peristiwa istimewa. Stasiun berita TV One bahkan sampai membuat siaran langsung. TV One bahkan mengangkat topik itu dalam program talk show Indonesia Lawyer Club (ILC). TV One banjir pujian karena keberaniannya menentang arus.
Namun Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menanggapinya dengan biasa-biasa saja. “Dear Pemirsa TV One; Terima kasih atas semua atensi dan apresiasi. Sesungguhnya kami hanya menjalankan tugas jurnalistik: memberitakan peristiwa yg terjadi di ruang publik. Tidak lebih, “ tulis Karni di akun twitternya.
Bukan untuk pertamakali
Bila kita membuka-buka kembali arsip lama, ternyata bukan hanya kali ini saja Kompas mengabaikan Reuni 212. Pada tahun 2017 Kompas juga tidak memberi porsi peristiwa tersebut di halaman muka.
Pada edisi Ahad 3 Desember 2017 Kompas memilih foto peristiwa peringatan puncak Hari Guru sebagai foto utama. Dari sisi berita, peristiwa tersebut tidak aktual. Hari Guru jatuh setiap tanggal 25 November. Pada tahun lalu diperingati pada tanggal 2 Desember bersamaan dengan Reuni 212.
Hanya pada Aksi 212 tahun 2016 Kompas memberi porsi berita sangat besar di halaman utama. Kompas memuat judul besar “Terima Kasih” dilengkapi dengan foto yang ikonik lautan massa di Monas. Pada foto bawah terlihat Presiden Jokowi berjalan di bawah guyuran hujan menuju Monas.
Mengapa sikap Kompas yang tidak memberitakan peristiwa Reuni 212 menjadi sorotan dan perhatian publik? Sebagai media, Kompas adalah media cetak terbesar dan terpenting di Indonesia. Sikap dan pilihan politiknya akan sangat menentukan. Kompas juga mempunyai sejarah panjang dalam jatuh bangunnya pergulatan pers Indonesia.
Mengutip laman wikipedia ide awal penerbitan harian Kompas datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Xaverius Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen.
Ahmad Yani menginginkan ada media yang bisa menandingi wacana Partai Komunis Indonesia. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, Peter Kansius Ojong (Auwjong Peng Koen), seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, dan Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik.
Singkat cerita koran yang semula akan diberi nama Bentara Rakyat itu terbit sebagai corong Partai Katolik. Nama yang dipilih Kompas, sesuai pemberian Presiden Soekarno. Pemimpin Redaksi pertamanya adalah Jacob Oetama.
Dengan latar belakang Kompas seperti, dugaan adanya faktor “kesengajaan” menenggalamkan berita Reuni 212 menjadi sangat sensitif.
Kompas harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa kebijakan redaksinya benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip jurnalistik yang universal. Bukan hanya karena ingin menjilat penguasa, seperti telah diingatkan oleh P.K. Ojong, apalagi pilihan ideologis karena berseberangan dengan para pendukung Reuni 212.
Bila benar itu pilihan ideologi dan politik, maka akan menjadi semacam “bunuh diri” jurnalisme ala Kompas. end